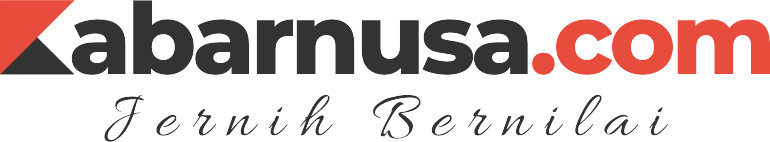Jakarta – Setiap tanggal 8 Juni diperingati dunia sebagai Hari Laut Sedunia. Untuk Indonesia, ini bukan sekadar perayaan simbolik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai sepanjang 108 ribu km (KKP, 2023), Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis dan kekayaan laut yang luar biasa.
Namun, fakta ini kontras dengan arah pembangunan yang justru kerap mengancam keberlanjutan ekosistem laut itu sendiri.
Potensi laut Indonesia memang besar. Kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023) memperkirakan potensi ekonomi kelautan bisa mencapai USD 1,33 triliun per tahun.
Indonesia juga menjadi pusat segitiga terumbu karang dunia atau Coral Triangle yang menyimpan sekitar 76% spesies karang global (WWF, 2022). Tapi, apakah kita sudah menjaganya dengan baik? Faktanya, berbagai kebijakan pemerintah justru berpotensi merusak laut. Salah satunya adalah eksplorasi tambang nikel oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT ANTAM Tbk di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pulau kecil ini masuk kawasan konservasi dan punya keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Setelah sempat dihentikan lewat Keppres No. 41/1999, PT Gag Nikel kembali aktif sejak memperoleh izin operasi produksi pada 2017 dengan luas konsesi 13.000 hektare (Tempo, 2023; Mongabay Indonesia, 2023).
Proyek ini menuai kritik keras. Laporan JATAM Papua Barat (2023) menunjukkan indikasi pencemaran perairan, sedimentasi yang meningkat, hingga potensi kerusakan terumbu karang akibat aktivitas tambang. Masyarakat adat juga menilai proses perizinan tak transparan dan minim pelibatan warga setempat. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tapi juga soal hak dan keadilan.
Kebijakan kontroversial lainnya adalah dibukanya kembali ekspor pasir laut melalui PP No. 26 Tahun 2023. Padahal, larangan sebelumnya diterapkan sejak 2003 karena penambangan pasir laut terbukti merusak habitat pesisir, mempercepat abrasi, dan mengancam keberadaan biota laut seperti lamun dan mangrove. Data Walhi (2023) menyebutkan, Indonesia kehilangan sekitar 42% tutupan lamun dalam dua dekade terakhir.
Berbagai masalah ini mengindikasikan bahwa pembangunan kelautan kita belum berorientasi pada keberlanjutan. Padahal, pakar seperti Christian Bueger dan Timothy Edmunds (2017) menekankan bahwa keamanan maritim di abad 21 harus mencakup perlindungan ekosistem laut, bukan hanya patroli kapal dan kedaulatan wilayah.
Sementara itu, Jaleswari Pramodhawardani (2019) dalam kajian geopolitiknya menegaskan bahwa posisi Indonesia di jalur strategis Indo-Pasifik harus dibarengi dengan tata kelola laut yang adil secara ekologis.
Hari Laut Sedunia seharusnya jadi momen reflektif bagi kita semua.
Pemerintah harus mulai mengevaluasi proyek-proyek ekstraktif di wilayah laut dan pulau-pulau kecil, serta menghentikan kebijakan yang justru membuka celah bagi kerusakan ekologis. Kita perlu kebijakan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga adil untuk generasi mendatang dan menjaga daya dukung lingkungan.
Indonesia tak bisa lagi memposisikan laut hanya sebagai sumber tambang atau pasir. Laut adalah ruang hidup, ruang budaya, dan ruang masa depan. Sebagai bangsa maritim, saatnya kita bangun kesadaran ekologis sebelum semuanya terlambat.***