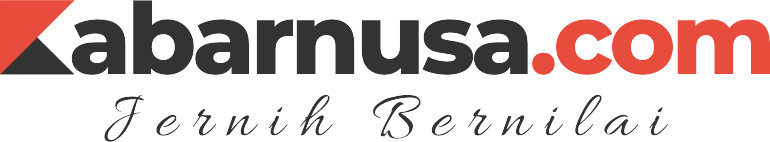Jakarta – Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan jangka panjang. Dalam konsep ini, pembangunan yang dilakukan harus memenuhi kebutuhan sekarang (jangka pendek), namun tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.
Konsep pembangunan ini masih kurang diterapkan di Indonesia. Hal itu terbukti kurang diperhatikannya aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan sehingga menyebabkan banyak kerugian yang dialami oleh negara. Pada tahun 2023 tercatat 3.383 kejadian bencana di Indonesia dengan 1.492 di antaranya berupa banjir (BNPB, 2024).
Selain itu, sekitar 30% sumber air permukaan di Indonesia telah tercemar limbah industri maupun rumah tangga (KLHK, 2023). Kekurangan air bersih untuk pertanian, bencana kekeringan maupun banjir merupakan dampak dari pembangunan yang tidak mengedepankan konsep berkelanjutan Geografi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari aspek fisik dan non-fisik suatu wilayah, menawarkan sebuah perangkat pembangunan yang cukup holistik.
Dengan penggunaan ilmu geografi, pembangunan menjadi terintegrasi antara pengelolaan fisik dan pengelolaan manusia di dalamnya. Hasil kajian geografis seperti karakteristik batuan, karakteristik tumbuhan, karakteristik iklim, dan perilaku masyarakat di suatu wilayah, dengan menggunakan metode analisis geografis, dapat dijadikan acuan pembuatan kebijakan regulasi pemerintah setempat.
Ilmu Geografi berperan dalam membentuk konsep pembangunan holistik yang mengedepankan integrasi semua aspek, baik fisik maupun non-fisik. Indonesia telah menetapkan visi besar “Indonesia Emas 2045” untuk menjadi negara maju, sejahtera, inklusif, dan berdaya saing tinggi pada peringatan 100 tahun kemerdekaan.
Visi ini mencakup empat pilar utama: (1) pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan; (3) pemerataan pembangunan; serta (4) ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada sejauh mana mampu mengintegrasikan keempat pilar ini karena fokusnya pada hubungan ruang, lingkungan, dan manusia.
Potensi Indnesia memang besar. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 278,7 juta jiwa (BPS, 2023), terbesar ke-4 di dunia. Luas daratan mencapai 1,91 juta km² dan lautan 6,32 juta km², dengan garis pantai sepanjang 108 ribu km—terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (KKP, 2023). Indonesia juga memiliki cadangan nikel terbesar dunia, sekitar 21 juta ton (USGS, 2023), yang menjadi kunci transisi energi global. Sektor pertanian masih menyerap 29% tenaga kerja nasional (BPS, 2023), sementara perikanan menyumbang Rp873 triliun terhadap PDB nasional (KKP, 2023).
Namun, potensi ini juga diiringi risiko besar. Indonesia termasuk dalam 35 negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia (INFORM Risk Index, 2023). Rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia mencapai Rp22,3 triliun per tahun (Bappenas, 2022). Selain itu, disparitas pembangunan masih lebar: rata-rata PDRB per kapita di Jawa mencapai Rp75 juta, sementara di Papua hanya sekitar Rp30 juta (BPS, 2023).
Pemanfaatan geografi dan teknologi geospasial dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Sektor geospasial diperkirakan berkontribusi Rp3.200 triliun per tahun bagi perekonomian Indonesia (BIG, 2022). Dengan peta keruangan yang detail, pemerintah bisa merencanakan pembangunan berbasis mitigasi bencana, pengendalian lingkungan, hingga tata kelola sumber daya alam yang lebih adil.
Pendidikan geografi juga krusial. Saat ini tingkat literasi lingkungan masyarakat Indonesia masih rendah, hanya 47,5 dari skala 100 (UNESCO ESD Report, 2022).Untuk mencapai target Indonesia Emas 2045, kesadaran spasial dan lingkungan perlu ditanamkan sejak dini melalui kurikulum pendidikan.
Geografi mendukung pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK melalui pendidikan dan riset spasial, pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam, pemerataan pembangunan melalui perencanaan berbasis wilayah, serta ketahanan nasional melalui geostrategi dan pengelolaan perbatasan. Tanpa pendekatan berbasis geografi, pembangunan akan cenderung timpang, eksploitatif, dan tidak berkelanjutan.
Ilmu geografi menjadi fondasi penting dalam mengintegrasikan keempat pilar ini. Geografi tidak hanya mempelajari bentuk dan fenomena permukaan bumi, tetapi juga memberikan solusi berbasis ruang untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan pemanfaatan teknologi geospasial dan pemahaman keruangan yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 secara inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan jangka panjang. Pembangunan yang dilakukan harus memenuhi kebutuhan sekarang dan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.
Pemetaan dan pengelolaan sumberdaya alam menjadi penting karena berkaitan dengan pembangunan keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan kandungan Asta Cita Presiden Prabowo saat ini. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tidaklah mustahil kalau dilihat dari potensi yang dimiliki.
Letak Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, garis pantai terpanjang kedua di dunia, sumber daya alam melimpah seperti tanah subur, hasil laut, dan mineral berharga. Sebagai negara yang berada di pertemuan lempeng tektonik besar dunia dan wilayah tropis membuat berbagai jenis sumberdaya alam ada di Indonesia baik biotik maupun abiotik.
Kekayaan dan keberagaman sumberdaya alam tersebut adalah anugerah besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Potensi ini mendukung sektor pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan perdagangan internasional.
Akan tetapi kondisi ini juga bisa berubah menjadi bencana jika saja gagal dalam mengelola keberadaan sumberdaya alam tersebut sehingga target Indonesia Emas sulit tercapai. Geografi Ilmu yang memetakan dan menganalisis sumber daya alam, sehingga penggunaannya dapat berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.
Disisi lain lokasi geologi dan geografis Indonesia juga membawa risiko tinggi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Risiko tinggi akan bencana alam tersebut membawa pembangunan perlu mempertimbangkan mitigasi bencana.
Disparitas pembangunan, degradasi lingkungan yang terjadi meminta terlaksananya konsep pembangunan berkelanjutan. “Indonesia Emas 2045 dengan keempat pilar pada visi besar tersebut memerlukan analisis keruangan, pemanfaatan data geospasial, dan integrasi perencanaan berbasis wilayah. Semuanya ini adalah inti kajian ilmu geografi.
Pemanfaatan data geospasial dan Sistem Informasi Geografis (GIS) menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan. Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatat pemanfaatan data geospasial berkontribusi hingga Rp3.200 triliun per tahun terhadap perekonomian nasional (BIG, 2022).
GIS membantu dalam mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan berbasis data. Misalnya, analisis keruangan berhasil mengidentifikasi 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia (KLHK, 2023) serta 2,9 juta hektar kawasan rawan banjir (BNPB, 2024).
Pembangunan berkelanjutan membutuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran yang baik terhadap lingkungan. Indeks Literasi Lingkungan Indonesia masih 47,5 dari skala 100 (UNESCO, 2022), menunjukkan perlunya pendidikan geografi yang lebih kuat.
Karenanya, Pendidikan Geografi dalam menyambut Indonesia Emas 2045 menjadi sebuah keniscayaan yang perlu ditanamkan pada semua jenjang pendidikan. Sebagai pembanding, Jepang memasukkan pendidikan mitigasi bencana berbasis geografi ke dalam kurikulum nasional sejak 1995, yang berkontribusi menurunkan tingkat korban jiwa akibat bencana hingga 40% (UNDRR, 2020).
(Prof. Muzani Jalaluddin, M.Si, guru besar geografi kebencanaan, Universitas Negeri Jakarta)