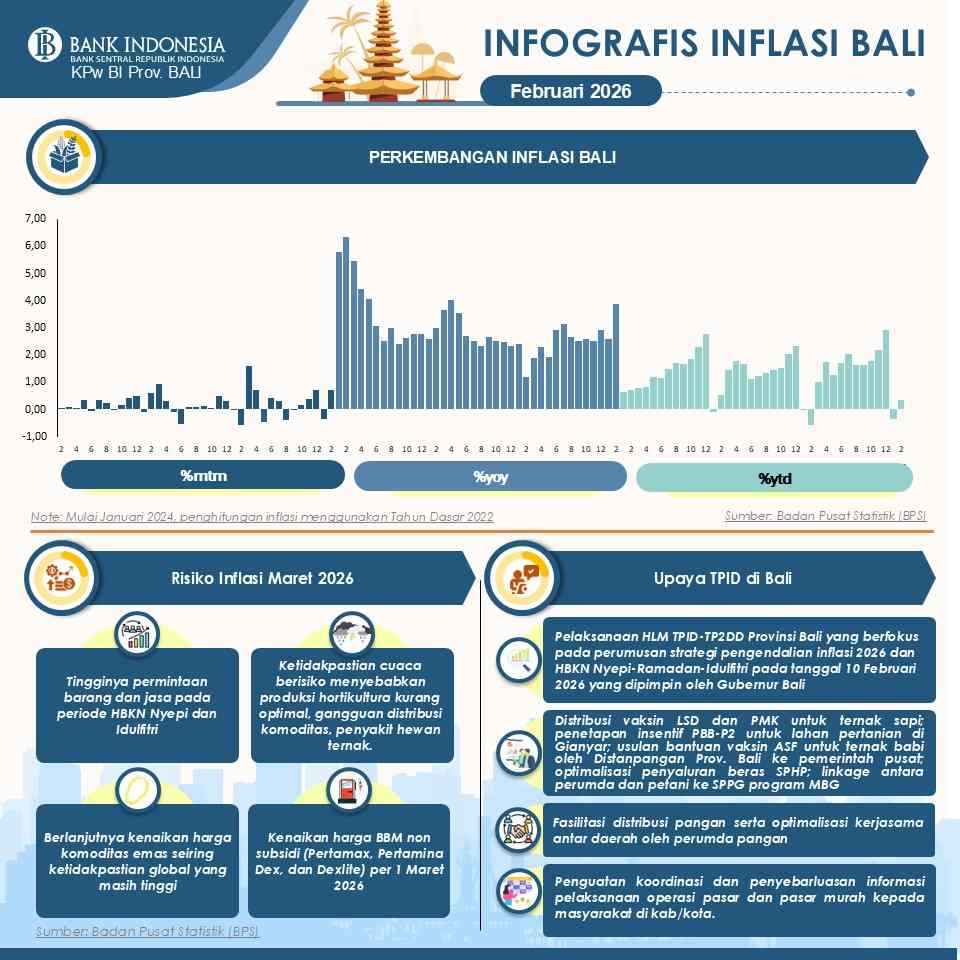Yogyakarta – Rencana pemerintah membangun rumah bersubsidi berukuran 18 meter persegi telah memicu gelombang kritik dan perdebatan sengit di masyarakat. Ukuran yang terbilang mungil ini menimbulkan pertanyaan: apakah ini solusi hunian layak atau justru bibit masalah baru di masa depan?
Menanggapi polemik yang memanas ini, pakar Teknik Arsitektur UGM, Ir. Ikaputra, angkat bicara. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya, ukuran 18 meter persegi bisa jadi diterima, namun dengan catatan besar: harus dirancang sebagai bagian integral dari konsep rumah tumbuh yang terstruktur, didukung oleh luasan tanah yang memadai.
“Delapan belas meter persegi itu adalah standar minimum internasional untuk hunian darurat pascabencana. Konteksnya bukan untuk permanen,” tegas Ikaputra kepada wartawan di Kampus UGM, Kamis (3/7). “Jika memang ingin digunakan untuk jangka panjang, maka perencanaan tumbuhnya harus jelas.”
Ikaputra menjelaskan bahwa rumah seluas 18 meter persegi lazim digunakan sebagai hunian awal bagi korban bencana karena situasinya yang darurat. Namun, jika konsep ini dipaksakan untuk penyediaan rumah permanen, maka sejumlah catatan krusial wajib diperhatikan.
Menurut Ikaputra, kunci keberhasilan model rumah mini ini terletak pada rancangan rumah tumbuh, di mana rumah dibangun secara bertahap sesuai kemampuan ekonomi pemilik. Namun, ia secara tegas mengkritik keterbatasan lahan yang disiapkan. Bayangkan, jika rumah dibangun di atas lahan seluas 25 meter persegi, hanya tersisa 7 meter persegi sebagai ruang tumbuh – sebuah kondisi yang jauh dari ideal!
“Masalahnya bukan di rumah 18 meter perseginya, tapi di lahannya yang terlalu sempit,” ungkapnya dengan nada prihatin. “Idealnya, lahan harus bisa mengakomodasi pengembangan setidaknya dua kali lipat dari bangunan awal, bahkan ditambah ruang terbuka hijau.”
Ikaputra menyarankan bahwa luasan minimum lahan yang memadai adalah sekitar 50 meter persegi. Ukuran ini memungkinkan pertumbuhan bangunan, penambahan ruang bertahap sesuai kebutuhan keluarga, serta keberadaan pohon dan sistem drainase yang sehat. Jika tidak, ia memperingatkan, risiko munculnya kawasan padat dan kumuh akan meningkat drastis.
Selain rumah tumbuh horizontal, Ikaputra juga mengusulkan alternatif lain: pembangunan rumah susun sewa (rusunawa). Solusi ini, menurutnya, sangat relevan terutama jika tanah di kawasan perkotaan sangat terbatas dan mahal. Rusunawa bisa menjadi jawaban yang efisien asalkan dilengkapi dengan akses transportasi publik yang terjangkau.
“Kalau rumah susun dibangun di pinggiran kota yang harga tanahnya lebih murah, maka harus ada akses yang mudah ke tempat kerja, seperti stasiun atau angkutan umum murah sehingga efisien bagi semua pihak,” terangnya.
Lebih lanjut, Ikaputra menggarisbawahi pentingnya rencana pertumbuhan rumah sejak tahap awal. Ini bukan hanya tentang struktur bangunan yang aman, terutama terhadap gempa, tetapi juga penataan ruang yang mendukung kehidupan keluarga secara berkelanjutan.
Ia berbagi pengalaman UGM dalam membangun rumah pascabencana gempa di Yogyakarta dan letusan Merapi, yang menunjukkan bahwa rumah tumbuh bisa berhasil jika desain arsitektural dan strukturalnya dirancang sejak awal.
“Yang penting bukan hanya besar rumahnya, tapi bagaimana rumah itu bisa berkembang dengan aman dan manusiawi,” pungkasnya. “Perencanaannya ini penting dan harus jelas dari awal karena rumah layak bukan hanya soal luas, tapi juga soal hidup yang layak di dalamnya. Jangan sampai niat baik menghadirkan hunian malah berujung pada kawasan yang tidak layak.”
Polemik rumah subsidi 18 meter persegi ini jelas menyoroti perlunya pertimbangan matang antara efisiensi biaya dan kualitas hidup penghuninya ***