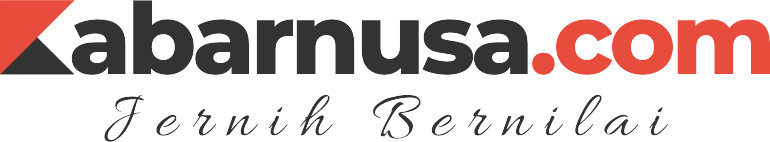|
| ilustrasi/net |
Tanggal 12 Juli 2020 adalah Hari Koperasi yang ke-73 Tahun, walaupun bangsa Indonesia tak merayakannya secara meriah, namun kinerja dan sumbangsihnya pada perekonomian bangsa cukup signifikan.
Koperasi adalah badan usaha yang disebut dalam UUD dan acap disebut sebagai soko guru perekonomian nasional .
Koperasi di Indonesia sudah terbukti banyak menyejahterakan anggota. Salah satu indikator adalah adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan kepada anggota. Dan, tidak benar bahwa Koperasi di Indonesia tidak terbukti menyejahterakan anggotanya melalui salah satu indikator Sisa Hasil Usaha (SHU).
Banyak koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip badan usaha Koperasi justru berkembang dan maju, di era Orde Baru kita mengenal Koperasi Peternakan dan Susu di Lembang, Provinsi Jawa Barat, dan di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, serta ada Koperasi Batik di Yogyakarta dan Solo. Koperasi Batik justru punya gedung monumental GKBI di bilangan Semanggi.
Setelah Orde Reformasi, ditandai liberalisasi ekonomi, ekspose keberhasilan (success factor) tidak dimunculkan. Padahal masih ada koperasi non simpan pinjam (selain Kospin Jasa) yang maju, seperti Koperasi Pusat Susu Bandung Utara Lembang yang meraih dua penghargaan sebagai koperasi produsen dengan Aset dan Volume Usaha Terbesar,berdiri pada tanggal 8 Agustus 1971 dan memiliki jumlah anggotanya sekitar 8.509 orang per Tahun 2017.
Kegiatan usaha KPSBU Lembang meliputi usaha simpan pinjam, perdagangan susu, penyediaan makanan ternak atau biasa disebut MAKO (Makanan Koperasi), pembibitan dan kesehatan hewan, dan usaha perdagangan.
Disamping kegiatan usaha, pengurus koperasi juga giat mendorong peternak utk membangun reaktor Biogas Rumah (BIRU).
Koperasi Agro Niaga Jabung Malang Jawa Timur meraih penghargaan sebagai koperasi produsen dengan CSR Terbaik pada Tahun 2017 dan masih banyak yang lainnya.
Tidak semua koperasi adalah jenis simpan pinjam, namun alasan akses ke kredit perbankan yang sulitlah membuat koperasi “menolong” dirinya sendiri) dalam pembiayaan organisasinya, terlebih skema pinjaman atau kredit lembaga perbankan tidak sesuai dan cocok dengan koperasi. Data koperasi non simpan pinjam di atas menjadi bukti bahwa koperasi juga berhasil di sektor lainnya.
Namun anehnya, pada Hari Koperasi 2016, Presiden Jokowi melontarkan gagasan “Mengkorporasi Koperasi” dengan tujuan agar koperasi bisa lebih memperhatikan aspek bisnis demi mendongkrak SHU anggota. Pernyataan salah kaprah yang menggejala ditengah publik (kalau tak tepat disebut salah besar) atas pengertian mengkoorporasikan koperasi harus dibenahi.
Adalah Presiden Joko Widodo setelah merayakan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Palangkaraya menyampaikan kolaborasi Hutan Tanaman Rakyat dan Industri Kayu dengan para petani pemegang izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada Selasa, 20 Desember 2016. Presiden saat itu sambil menyerahkan Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas seluas 1.885 hektar kepada 183 orang.
Kemudian, Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPBD) Desa Lawang Taman dan Tumbang Manyarung Kabupaten Kapuas seluas 2.587 hektar kepada 286 orang, Hutan Desa Rabambang, Harowu, Rangan Hiran di Kabupaten Gunung Mas seluas 3.046 hektar kepada pemegang izin 238 orang, Hutan Desa Tangkehan, Tumbang Tarusan, Tambak dan Bawan di Kabupaten Pulang Pisau seluas 2.016 hektar kepada 931 pemegang izin.
Pada kesempatan tersebut Presiden menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk Perhutanan Sosial yang akan diberikan hak pengelolaannya kepada rakyat, petani, kelompok tani dan koperasi. Melalui Perhutanan Sosial, kita ingin mengkorporasikan petani dan mengkorporasikan koperasi. Kita ingin mengembalikan kejayaan industri kehutanan dengan basis kehutanan rakyat. Izin pengelolaan hutan (konsesi) diberikan kepada rakyat.
Hasil kayunya diolah oleh perusahaan yang berorientasi ekspor. Oleh karena itu kolaborasi ini sangat tepat, kolaborasi antara Hutan Tanaman Rakyat dengan industri kayu, agar kejayaan industri kehutanan dapat kembali kita raih. demikian tegas Presiden Jokowi.
Pernyataan Presiden soal mengkorporasikan koperasi ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dengan menggandeng Agriterra, badan pertanian dari Belanda dalam pengembangan korporasi petani berbasis koperasi di Indonesia. Disampaikan pula oleh Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Victoria BR Simanungkalit bahwa kerjasama tersebut guna mendukung upaya dalam mengkorporasikan pertanian, pada acara penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Agritera tanggal 27 Nopember 2018 di Jakarta.
Lalu, tepatkah istilah mengkorporasikan koperasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan ditelan “mentah-mentah” begitu saja oleh pejabat Kementerian Koperasi dan UMKM?
*Memahami Koperasi*
Berdasarkan kata asalnya, Koperasi adalah istilah serapan yang berasal dari Bahasa Inggris “cooperative”, yang secara umum pengertiannya bekerjasama. Sedangkan korporasi berasal dari kata “coorporation” yang berarti adalah korporasi atau secara umum dikenal dengan perusahaan besar yang didirikan oleh individu-individu pemilik modal (capital) dan dilekatkan pada negara-negara yang menjalankan praktek ekonomi sistem kapitalisme. Dari 2 (dua) kata serapan ini saja orang awam sudah bisa menyimpulkan bahwa kata-kata ini memiliki makna yang berbeda, bagaimana bisa kemudian muncul kalimat mengkorporasikan koperasi?
Berdasar latar belakang sejarah pendirian dan motif serta tujuan organisasi koperasi dan korporasi jelas berbeda secara diametral dan mendasar. Koperasi didirikan atas dasar inisiatif dan partisipasi dari beberapa individu untuk tujuan menolong diri sendiri (self help) dan tolong menolong antar anggota (membership). Sementara korporasi didirikan oleh individu yang memiliki modal (capital ownership) melalui pembentukan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan tujuan mencari laba sebesar-besarnya untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (stockholder).
Latar belakang sejarah Indonesia dimasa kolonialisme Belanda, juga diawali oleh gerakan perdagangan dunia yang dilakukan oleh VOC sebiah korporasi yang memiliki hak monopoli perdagangan di wilayah bagian barat dunia kala itu. Dan, koperasi tumbuh dan berkembang saat masa penjajahan Belanda adalah dalam rangka “melawan” penindasan dan kekejaman korporasi Belanda pada bumi putera melalui skema utang-piutang seperti rentenir.
Jadi, mengkoorporasikan koperasi seperti apa yang hendak dimaksudkan Presiden dan Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)? Kalau cuma untuk menjalankan prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi bisnis atau entitas ekonomi, justru koperasi lebih dulu menerapkan prinsip-prinsip ini sejak pendiriannya.
Yang tidak atau belum dimiliki oleh koperasi selama ini, yaitu kepemihakan kebijakan (affirmative policy) pemerintah atas entitas ekonomi yang prinsipnya termaktub pada Pasal 33, ayat 1 UUD 1945. Justru otoritas koperasi membiarkan praktek-praktek penyimpangan yang terjadi atas nama badan usaha koperasi, tapi cara dan proses kerjanya tak berbeda dengan korporasi. Mendesaknya (urgent) revisi UU 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan pengganti UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh sangat dibutuhkan. Sehingga salah kaprah istilah (gramatical) dan sejarah koperasi dan korporasi tidak terlanjur meluas menjadi kebiasaan yang salah dalam memahaminya, dan menimbulkan pemahaman yang salah secara massif pada publik. Bahwa Koperasi dan Korporasi itu berbeda dan tidak bisa Koperasi dikoorporasikan secara prinsip.
*Tujuan Koperasi*
Tujuan koperasi didirikan adalah untuk membangun ekonomi para anggotanya melalui kegiatan usaha atau bisnis, jadi orientasi SHU yang sebesar-besarnya bukan indikator utama meskipun tak dipungkiri setiap Rapat Anggota Tahunan sebagai forum tertinggi koperasi ada keputusan pembagian SHU. Tujuan mengkorporasikan koperasi tidak saja telah tidak sesuai dengan prinsip pendirian koperasi, tapi justru merendahkan martabat bangun usaha koperasi itu sendiri.
Soal kemajuan dan perkembangan usaha harus diupayakan dengan menerapkan ilmu manajemen dan tidak harus mengubah atau menjadikan koperasi seperti korporasi yang sangat berbeda secara diametral dan mendasar. Justru kalau koperasi hanya merubah prinsipnya, maka bangun usahanya bukan lagi koperasi.
Koperasi adalah kumpulan orang, korporasi kumpulan modal, oleh karena itu koperasi tidak bisa dan tidak mungkin di korporasikan.
Usaha Kementerian Koperasi dan UKM agar koperasi tidak lagi inferior, melainkan menjadi badan usaha yang setara dengan korporasi,bukan saja salah kejadian. Namun, juga menunjukkan pejabat Kementerian Koperasi dan UKM tidak memahami dan tidak mampu membedakan prinsip koperasi di satu sisi dan korporasi di sisi yang lain. Jelas tidak tepat menjadikan koperasi sebagai korporasi, secara normatif kebijakan ini menyimpang dari prinsip badan usaha koperasi.
Yang dituntut oleh publik adalah usaha dan upaya Kemenkop UKM harus diarahkan untuk menjadi fasilitator bagi kebijakan perkoperasian yang lebih kondusif, inilah masalah utamanya. Jika kebijakan terhadap koperasi dan akses ekonomi yang diberikan setara dengan korporasi, maka koperasi jauh lebih unggul di masa depan. Hal mana telah dibuktikan oleh koperasi di negara-negara lain, yang justru berada dalam sistem ekonomi kapitalisme tapi kebijakan pemerintahnya mengakomodasinya.
Setelah UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi, pada bulan Mei 2014, maka tentu UU Perkoperasian yang berlaku adalah UU sebelumnya yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992.
Saat ini belum ada upaya untuk mengamandemen Pasal 33 UUD agar kembali mencantumkan kata koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Ayat (1) dan ayat (4) telah dipersepsikan secara tidak menyatu (konkruen). Pada ayat (1) disebutkan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedang pasal (4) berbunyi “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, serta tidak ada kata koperasi.
Seharusnya kata koperasi yang sebelumnya ada dalam penjelasan Paaal 33 UUD 1945 dikembalikan, dan yang lebih penting adalah Indonesia harus merumuskan UU tentang Sistem Ekonomi Nasional sebagai turunan dari Pasal 33 dan menjadi rujukan bersama dalam pengaturan kebijakan perekonomian nasional, menjadi jelas tidak menerapkan praktek sistem ekpnomi kapitalisme maupun komunisme dan yang lainnya.
Apalagi secara kuantitatif, berdasar data Kemenkop UKM Per Juni 2019, jumlah koperasi mencapai 126.343 unit, turun dari 2014 sebanyak 212.570 unit. Ukuran kesehatan koperasi sangat berbeda dengan korporasi, kesehatan koperasi tidak hanya dinilai secara kuantitatif ansich, terlebih penting koperasi memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota bukan kepada yang punya modal atau kapital. Jumlah koperasi di Indonesia selama empat tahun ini (2014-2018) mengalami penurunan yang cukup drastis.
Dulu jumlah koperasi mencapai lebih dari 212 ribu unit, maka saat ini turun menjadi 138.400 koperasi.
Penurunan ini terjadi sejak dilakukan reformasi total pada koperasi di Indonesia mulai 2016 lalu. Meski demikian, omzet koperasi-koperasi di negara ini justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Diantaranya Koperasi Telekomunisasi Seluler yang masuk urutan 94 dengan omzet mencapai Rp 6,4 triliun dan memiliki 5 anak perusahaan. Selain itu Koperasi Sidogiri di Pasuruan yang memiliki omzet sebesar Rp 19 triliun dan 278 kantor cabang.
“Ada juga koperasi semen gresik yang masuk 300 koperasi besar dunia dengan omset Rp 2,5 Triliun. Total omzet koperasi Indonesia mencapai lebih dari Rp 30 Triliun. Bahkan di era 1990-an banyak koperasi mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk mahasiswa yang memiliki omzet sampai Miliaran rupiah, diantaranya adalah Koperasi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada/Kopma UGM, Kopma Universitas Brawijaya, Kopma Universitas Jenderal Soedirman, dan lain-lain.
Koperasi di Indonesia juga memberikan lapangan pekerjaan secara luas, banyak karyawan yang bekerja di koperasi, dan jumlah karyawan yang bekerja di unit usaha atau usaha yang dijalankan oleh koperasi. Data Kemenkop UKM per Juni 2019, menunjukkan jumlah total anggota koperasi adalah 22 juta orang lebih.
Sayangnya, kinerja koperasi juga dinodai oleh penipuan berkedok koperasi di Indonesia yang cukup marak pada 10 tahun terakhir. Dalam kasus Indosurya, misalnya, tidak ada upaya serius yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi UKM untuk menetralisir kesan (image), bahkan membawanya ke meja hukum.
Banyak pihak yang “memanfaatkan” koperasi untuk tujuan bukan memajukan koperasi dan untuk ini lebih relevan penindakan hukum yang harus ditegakkan oleh Bank Indonesia dan OJK, serta pengawasan oleh Kemenkop UKM, pembiaran atas kasus-kasus ini oleh otoritas justru akan memperburuk posisi Kemenkop UKM.
Selain itu, produk UU Perkoperasian dan UU sektor ekonomi lainnya secara hukum tidak mendukung perkembangan koperasi menjadi sokoguru perekonomian bangsa, bahkan yang terakhir justru mempersulit pendirian badan hukum koperasi.
Semestinya Kemenkop UKM lebih berperan aktif dan menjadi garda terdepan pengembangan koperasi untuk bisa melakukan upaya kerjasama lebih luas dengan sektor ekonomi lainnya dan mendorong ruang bagi kesetaraan dalam kebijakan ekonomi nasional dalam hubungannya dengan akses pembiayaan dan kerjasama usaha. Sinergi BUMN dan Koperasi sebagai bangun usaha yang dimandatkan dalam konstitisi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 adalah tanggungjawab Kemenkpp UKM. (*)
* Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta