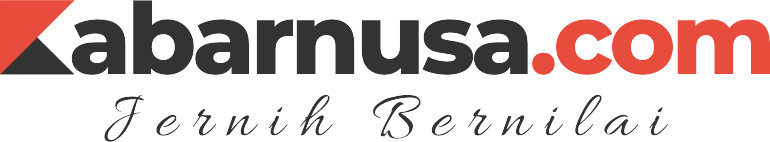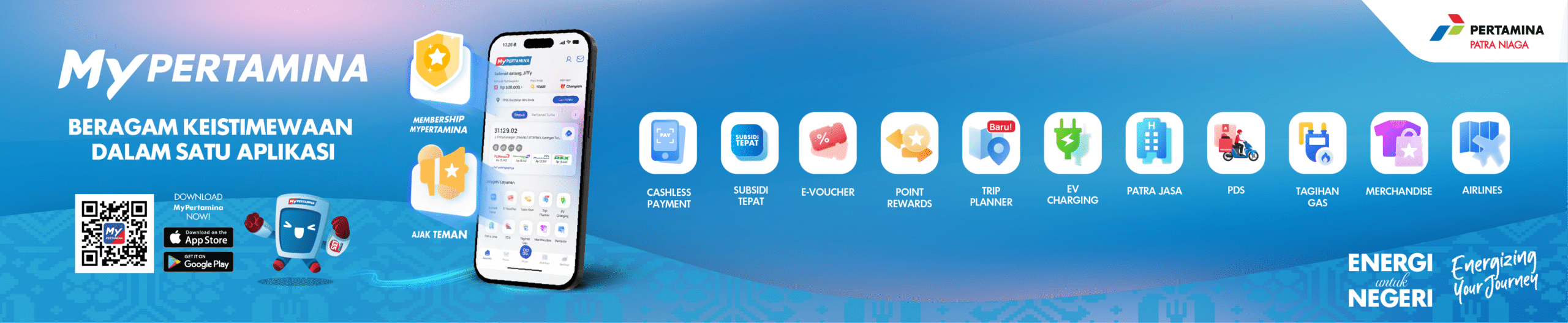|
| Defiyan Cori/ist |
Bulan November 2020 ini merupakan momentum yang istimewa bagi rakyat
dan bangsa Indonesia, sebab tanggal 10 Nopember merupakan peringatan Hari
Pahlawan ke-75 Tahun.
Penetapan peringatan Hari Pahlawan yang bertepatan pada Hari Selasa, tanggal
10 November 2020 itu didasari oleh Keputusan Presiden No. 316 Tahun 1959
tentang Hari-hari Nasional yang ditandatangani oleh Presiden pertama Republik
Indonesia, Ir.Soekarno (almarhum).
Ditetapkannya 10 November sebagai Hari Pahlawan bukanlah tanpa alasan, yaitu
oleh adanya peristiwa tanggal 10 November 1945 yang merupakan pertempuran
antara arek-arek Surabaya dengan tentara Belanda.
Pertempuran tersebut telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa pejuang yang
tewas saat melawan pasukan Netherlands-Indies Civil Administration (NICA) yang
membonceng pada sekutu.
Peristiwa itu merupakan reaksi dari kedatangan Tentara Sekutu ke Surabaya pada
Oktober 1945 yang dipimpin oleh Jenderal Mallaby dengan tujuan kembali ingin
menguasai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru 2 bulan
diproklamirkan kemerdekaanya.
Lalu, bagaimana memaknai Hari Pahlawan dalam perspektif pengelolaan Sumber
Daya Alam (SDA), kehadiran BUMN serta keberlanjutannya, terutama terkait
mandat konstitusi, Pasal 33 UUD 1945 sebagai hasil cipta, karsa dan karya para
pendiri bangsa (founding father), yang tentu saja sangat patut pula kita
pertahankan dengan segenap jiwa dan raga.
Artinya, Indonesia Yang Utama (Indonesia First) harus menjadi tujuan
pembangunan bangsa dan negara.
Penguasaan Cabang Produksi Penting
Pernyataan ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 jelas memerintahkan, bahwa: “Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan” yang secara
sederhana menafikkan kehadiran usaha orang per orang.
Apa saja kegiatan perekonomian yang harus disusun sebagai usaha bersama, maka
hal itu tertera pada ayat 2 dan 3 didalam pasal tersebut.
Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak
yang terdapat pada bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Terminologi penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting ini
kemudian dimandatkan pada perusahaan negara atau dikenal saat ini sebagai
Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selanjutnya publik dan pemangku kepentingan (stakeholders) juga harus memahami
alasan mendasar Pasal 33 UUD 1945 (konstitusi ekonomi) tentang kepentingan
perusahaan Negara memonopoli cabang-cabang produksi penting dan menguasai
hajat hidup orang banyak serta tidak serampangan atau gebyah uyah melakukan
penolakan monopoli konstitusional atau alamiah ini.
Latar belakang sejarah nasionalisasi BUMN-BUMN yang berasal dari
perusahaan-perusahaan swasta (korporasi) Belanda dan asing lainnya yang
melakukan kolonialisasi pada Ibu Pertiwi juga harus menjadi pertimbangan
penting.
Sebab, secara konseptual terdapat perbedaan cukup mendasar penguasaan
cabang-cabang produksi penting antara korporasi swasta yang dimiliki oleh
orang per orang dengan BUMN yang bukan perusahaan perorangan.
Selain BUMN adalah entitas ekonomi dan bisnis yang merupakan mandat konstitusi
ekonomi negara, juga merupakan agen bagi pembangunan ekonomi nasional sampai
ke pelosok negeri yang tak mungkin dilakukan oleh swasta yang mengutamakan
keuntungan (laba) sebesar-besarnya atas investasinya.
BUMN PT Pertamina dan PLN merupakan 2 (dua) unit perusahaan negara diantara
140 unit yang lainnya adalah bentuk penguasaan negara dalam cabang produksi
penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dijaga kehadiran dan
keberlanjutannya untuk mengemban penugasan negara sesuai Pasal 66 UU Nomor 19
Tahun 2003 tentang BUMN.
Sebab terdapat beberapa permasalahan yang harus dicarikan penyelesaiannya
terkait dukungan atas industri minyak dan gas bumi secara khusus dan energi
pada umumnya.
Salah satu permasalahan mendesak dan perlu penyelesaian segera terkait pasokan
minyak dan gas di dalam negeri, yaitu kondisi kilang-kilang yang ada saat ini
sudah berumur tua.
Akibatnya, hanya sedikit minyak mentah yang dapat diolah pada fasilitas
pengolahan milik perusahaan negara Pertamina tersebut sehingga tidak bisa
memenuhi seluruh permintaan konsumen dan harus melakukan impor.
Kondisi ini pernah disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati
sewaktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR-RI pada tanggal 5
Oktober 2020, kilang yang dimiliki pihaknya hanya mampu mengolah 3 persen
jenis minyak mentah atau sangat terbatas dibanding yang ada di dunia saat ini.
Disamping itu, Pertamina perlu bekerjasama dengan entitas ekonomi lainya untuk
mengelola blok-blok yang tidak lagi produktif agar beban biaya operasional
dapat diminimalisir. Pertamina harus memusatkan perhatian atau fokus pada
blok-blok yang menghasilkan lebih besar dan yang produktif.
Skala ekonomis sekarang yang tidak terpenuhi oleh blok-blok kecil yang
berproduksi 300-500 barel per hari sebaiknya dikelola berdasar prinsip usaha
bersama sehingga biaya-biaya pengadaan (procurement), teknis (engineering) dan
lain-lain lebih rasional.
Maka itu, peran pemerintah cq. Kementerian ESDM dalam hal ini sangat
diperlukan dalam memfasilitasi kebijakan penguasaan negara disektor migas ini
di satu sisi.
Sementara disisi yang lain, implementasi prinsip usaha bersama dengan
perusahaan lain atau swasta dengan pembagian (sharing) hasil dan manfaat
secara proporsional di hulu migas ini lebih relevan menjadi skema kerjasama.
Dengan demikian Pertamina tidak terlalu memiliki beban yang berat secara
ekonomi dalam mengelola hulu migas yang berakibat pada penetapan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM) dari faktor produksi hulu migas ini ke konsumen akhir di
hilirnya.
Sebagaimana halnya itu terjadi pada PLN yang sebagian besar sektor hulunya
(energi primer) sebagai faktor produksinya, yaitu batu bara yang dikuasai
sebagian besar oleh 7 (tujuh) korporasi swasta sehingga semakin mempersulit
keadaan keuangannya dengan beban utang yang ada.
Sinergi Hulu-Hilir Energi
Pengorbanan dan sikap kepahlawan dalam perspektif pengelolaan ekonomi yang
saat ini didominasi oleh paradigma sistem kapitalisme sangat relevan dilakukan
antar BUMN.
Dalam kerangka inilah, Pertamina tentu akan memiliki kekuatan lebih untuk
memaksimalkan kinerja lapangan-lapangan produksi dengan lebih baik karena
banyak sumber daya yang terlibat.
Disamping membangun sinergi di sektor hulu atas lapangan migas yang tidak
ekonomis, maka Pertamina dan PLN juga mendapat penugasan pelayanan (Public
Service Obligation/PSO) untuk memperluas keterjangkauan BBM dan listrik dengan
harga yang sama (satu harga) di berbagai daerah.
Dengan biaya distribusi dan logistik yang tidak mudah dan murah, penugasan BBM
satu harga yang didasarkan pada Perpres 19 Tahun 2014 tentang Penyediaan,
Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (diperbarui melalui
Perpres 43 Tahun 2018) Pertamina bahkan telah menuntaskan pembangunan SPBU BBM
Satu Harga per September 2020 di 172 titik lokasi yang tersebar di pelosok
wilayah Indonesia.
Begitu pula halnya dengan Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang diberikan
penugasan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengaliri 433 desa yang
belum teraliri listrik dengan mengucurkan dana sejumlah Rp 735 Miliar dan
harus selesai sebelum akhir Tahun 2020 meski di tengah pandemi virus corona.
Berbagau langkah efisiensi dan efektifitas organisasi serta terobosan
manajemen berhasil dilakukan dengan infrastruktur terbatas ke wilayah 3T
(Tertinggal, Terdepan dan Terluar), Sebuah pengorbanan dan sikap kepahlawanan
dalam pembangunan ekononi, khususnya sektor energi dari jajaran SDM BUMN yang
luar biasa pencapaiannya serta layak diapresiasi rakyat, bangsa dan negara.
Bahkan, ditengah gejolak harga minyak mentah dunia dan kemampuan berproduksi
(kilang dan lapangan atau blok migas) yang tidak ekonomis, maka tentu tidak
menguntungkan posisi Pertamina.
Walaupun sampai saat ini Pertamina berhasil berkinerja lebih baik dibanding
perusahaan (korporasi) swasta asing yang merugi sangat besar dan melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) para karyawannya, tapi itu tak terjadi pada
Pertamina.
Kerugian PT Pertamina (Persero) yang tercatat sekitar Rp 11 Triliun pada
Semester I/2020 terkait dengan penurunan jumlah penjualan BBM sebagai dampak
dari pandemi covid 19 pun lebih rendah dari perusahaan migas lainnya.
Mengupayakan berbagai antisipasi agar kerugian tak semakin besar memang harus
dilakukan secara simultan, salah satunya adalah membangun sinergitas antar
BUMN di hulu dan di hilir dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Di sektor hulu, Pertamina harus mengupayakan agar kerugian atas transaksi
perdagangan disebabkan faktor kurs rupiah terhadap dollar AS bisa dikurangi
dengan meningkatkan sinergitas pengolahan migas di satu sisi.
Di sisi yang lain belanja perusahaan, seperti untuk impor minyak mentah dan
bahan bakar minyak (BBM), dengan menggunakan mata uang dollar AS harus
dikurangi, dan pemerintah harus mendukung upaya ini dengan melarang impor BBM
oleh perusahaan dagang (trader) yang memasok ke Pertamina.
Oleh sebab itu, langkah renegosiasi kontrak yang menggunakan mata uang asing
untuk dibayar menggunakan rupiah harus diupayakan.
Di sektor hilir, sinergi dengan Koperasi dan UKM melalui kemitraan antara
Pertamina selaku Badan Usaha penyedia BBM dengan Pemerintah Desa dalam
memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan akses BBM
sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat di sekitar desa
harus dilakukan secara bertahap dan dievaluasi.
Program Pertashop ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Kementerian
Dalam Negeri dengan Pertamina Persero tanggal 18 Februari 2020 tentang
Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Peningkatan dan Pengembangan
Program Pertashop di Desa.
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan BBM didesa terutama di 3.827
kecamatan atau 53% Kecamatan di Indonesia yang belum terjangkau akses SPBU
dengan memanfaatan aset desa.
Pada tahap awal sebagai crash program, akan diluncurkan pembangunan pertashop
di 418 titik lokasi yangmana pembangunan fasilitas dan manajemen pengelolaan
akan dilakukan oleh Pertamina.
Kemudahan harus diberikan pada Koperasi sebagai entitas ekonomi usaha bersama
sebagaimana halnya sinergi antar BUMN, jangan sampai program pertashop yang
menjadi program elitis.
Tentu saja kalkulasi ekonomi melalui kajian yang komprehensif atas program
kemitraan disektor hilir dalam pelayanan penjualan BBM sampai ke berbagai desa
harus memperhitungkan jalur distribusi, penyimpanan (storage) terdekat dan
potensi pasarnya.
Apabila hal ini tidak dilakukan, maka kerugian tentu akan dialami oleh
Pertamina apabila sinergi antar BUMN sebagai bentuk pengorbanan dan
kepahlawanan dibidang ekonomi untuk turut memajukan perekonomian di desa-desa
berbagai daerah Indonesia tidak mendapat dukungan BUMN sektor lain serta tidak
berjalan dengan baik dan optimal.
Pilihan sinergi usaha atau kemitraan dengan badan usaha Koperasi dan tidak
hanya dengan UKM yang kepemilikannya perorangan adalah sebagai upaya untuk
membangun entitas ekonomi konstitusi dan meminimalisir potensi kerugian atau
resiko lain secara orang per-orang.
Pengorbanan dan kepahlawanan BUMN Pertamina dan PLN ditengah beban keuangan
yang berat akan menjadi ringan kalau sinergitas BUMN dan Koperasi juga
terbangun dengan baik.
Melalui perjuangan bersama, senasib sepenanggungan atau model sinergitas
ekonomi dalam konteks menjaga eksistensi dan keberlanjutan BUMN (yang
dinasionalisasi dari Belanda) sebuah keniscayaan.
Barangkali inilah hakikat kepahlawanan kekinian ditengah “pertempuran” ekonomi
yang hadir mendunia (globalisasi) pada abad 21 ditengah-tengah interaksi
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sehingga tidak kembali mengulangi
sejarah kelam dominasi korporasi swasta dan asing di cabang-cabang produksi
penting diera kolonialisme. (*)
* Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi, alumni Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta