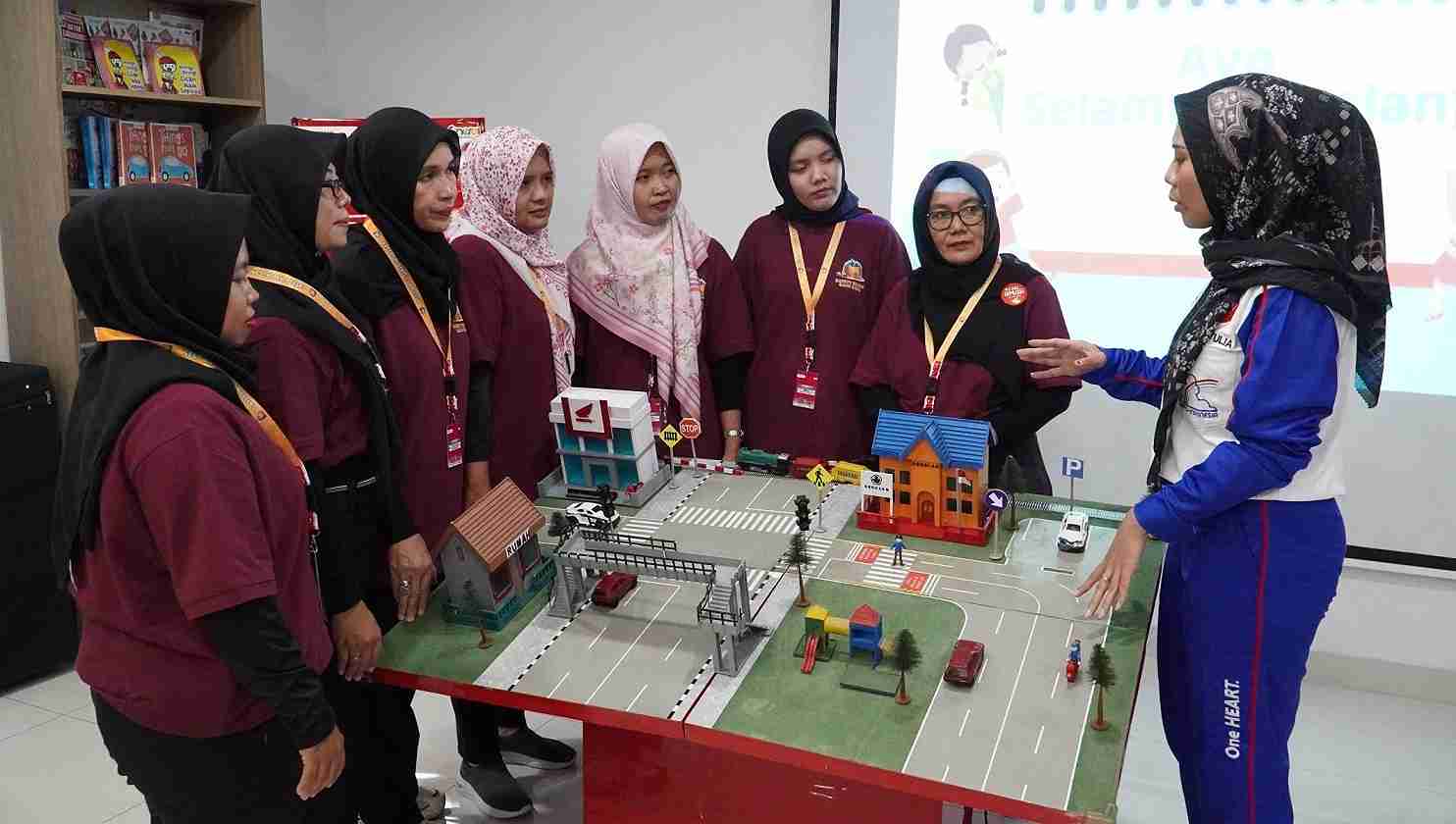|
| ilustrasi (foto:harian terbit) |
Kabarnusa.com – Kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia
semakin mengkhawatirkan dalam 10 tahun terakhir. TIndak kekerasan
dialami jurnalis terus meningkat dan ironisnya banyak dilakukan aparatur
negara kepolisian. Tak heran, jika kemudian dibanding negara lain,
dalam kebebasan pers dan bereskpresi Indonesia dalam zona merah.
Ketua
Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Suwarjono bersama Sekretaris
Jenderal Arfi Bambani Amri menyampaikan catatan kritis akhir tahun 2015,
dalam melihat kehidupan kebebasan pers dan berekspresi di zaman
Presiden Joko Widodo.
Melansir data World Press Freedom
Index 2015 yang dirilis Reporters Sans Frontiers (Prancis), posisi
Indonesia terbaru dalam kebebasan pers dan berekpresi berada di posisi
merah, ranking 138 dari 180 negara.
Posisi ini, bahkan berada di bawah Thailand (yang kini dipimpin junta militer), Taiwan dan India.
Sedangkan
Freedom House yang berbasis di Amerika Serikat, dalam lima tahun
terakhir menempatkan Indonesia dalam posisi partly free.
Indikator
yang mereka gunakan adalah pertama, kebebasan warga negara dan pers
terampas karena kehadiran undang-undang yang berpotensi membatasi
kebebasan berpendapat dan pers, seperti UU Informasi dan Transaksi
Elektronik.
Juga, UU Intelijen dan RUU Kerahasiaan Negara yang bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.
“Kedua,
media dan jurnalis rentan kekerasan dan kriminalisasi,” tegas Suwarjono
dalam siaran pers diterima Kabarnusa.com, Minggu (20/12/2015).
Dari dua faktor di atas, peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis mendorong Indonesia terpuruk dalam isu kebebasan pers.
Sepanjang
tahun 2015 ini, angka kekerasan terhadap jurnalis meningkat. Ada 43
kasus kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2015, meningkat dibanding
tahun 2014 yang mencapai 40 kejadian.
Namun satu yang
perlu dicatat, angka polisi sebagai pelaku kekerasan berlipat dua, dari
sebelumnya hanya enam kasus, kini tercatat ada 14 kejadian di mana
pelaku kekerasan adalah polisi.
Tujuh kejadian
kekerasan dilakukan orang tak dikenal, lima oleh satuan pengamanan,
empat oleh warga biasa, kepala daerah tiga kejadian, dan bahkan ada satu
pelaku adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Data
ini menunjukkan tidak adanya perubahan perilaku polisi dalam mengawal
kebebasan pers, sebagaimana diamanatkan UU No.40 tahun 1999, tentang
Pers.
“Kritik yang dialamatkan pada polisi, sebagai
salah satu pelaku kekerasan oleh berbagai pihak setiap tahun, tidak
diindahkan,” sebut Pemimpin Redaksi Suara.com itu.
Di
lapangan, polisi lebih brutal dalam bertindak. Kasus kekerasan terjadi
pada Sabtu (6/12/2015) di Pekanbaru, Riau adalah contohnya. Pengeroyokan
dilakukan polisi kepada jurnalis RiauOnline.co.id, Zuhdy Febryanto, terus berlangsung.
Meskipun
korban sudah menunjukkan identitasnya sebagai jurnalis. Zuhdy harus
dilarikan ke rumah sakit karena bocor di bagian kepala.
Daftar
kekerasan pada jurnalis oleh polisi yang terus memanjang, semakin
menjauhkan polisi dari tugas dan fungsinya, mengusut tuntas kasus
kekerasan pada jurnalis.
Delapan kasus “dark number”
kekerasan pada jurnalis yang menjadi beban polisi, terabaikan, dan tidak
ada tanda-tanda untuk diselesaikan.
Kedelapan kasus
itu adalah kasus Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) 1996, Naimullah (1997),
Agus Mulyawan (1999), Muhammad Jamaludin (2003), Ersa Siregara (2003),
Herliyanto (2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (2010), dan Alfred
Mirulewan (2010).
Di tahun yang sama, polisi juga
menjadi alat pemukul nara sumber media dengan melakukan upaya
kriminalisasi serampangan terhadap nara sumber dan pers.
Simak
saja kasus yang melibatkan dua komisioner Komisi Yudisial Suparman
Marzuki (Ketua) dan Taufiqurahman Sauri. Keduanya dilaporkan Hakim
Pengadilan Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi. Begitu juga kasus aktivis
Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo,
serta mantan penasihat KPK Said Zainal Abidin.
Ketiganya
dilaporkan Romli Atmasasmita, salah satu kandidat panitia seleksi
(pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketidaksetujuan Emerson,
Adnan dan Zainal Abidin direspon aksi kriminalisasi.
Kriminalisasi
terhadap jurnalis juga masih terjadi. Awal tahun 2015 ini, upaya
pemidanaan terhadap Pemimpin Redaksi Jakarta Post Meidyatama
Suryodiningrat atau Dimas dilakukan kepolisian dengan menetapkan status
tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
Meski
Dewan Pers sudah mengeluarkan permohonan penyelesaian kasus, namun
hingga kini masih menggantung. Kasus serupa terjadi di penghujung tahun
2015, Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan diadukan ke Mabes Polri
dengan tudingan telah mencemarkan nama baik Setya Novanto.
Terhadap
dua kasus ini seharusnya kepolisian mengacu putusan MA No
1608/K.Pid/2005 bahwa UU Pers disamakan dengan primat privilege,
didahulukan dari aturan pidana lain, jadi bila ada yang melapor harus
diselesaikan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.
Ini
juga merujuk MoU Dewan Pers dan Kepolisian RI tahun 2012 tentang
penanganan perselisihan atas pemberitaan untuk dilimpahkan kepada Dewan
Pers.
Pemerintah baru belum menunjukkan perkembangan
menggembirakan hal pemberian akses jurnalis asing untuk meliput di
Indonesia. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 482.3/4439/SJ
tentang penyesuaian prosedur kunjungan jurnalistik ke Indonesia menjadi
catatan tersendiri.
Melalui SE yang dikirimkan ke
semua kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten dan kota ini,
pemerintah melakukan pembatasan kerja jurnalis asing. Padahal
sebelumnya, pemerintah pernah diingatkan untuk menghapus clearing house
12 lembaga dan kementerian.
Clearing house ini adalah
forum untuk menakar pemberian izin jurnalis asing yang akan datang ke
Indonesia. Pengadilan dua jurnalis Inggris, Neil Richard George Bonner
dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser di PN Batam, Kamis 1 Oktober
2015.
Setelah 4 bulan ditahan karena meliput tanpa visa
kerja di Indonesia, adalah “korban” dari ketiadaan sistem yang
demokratis bagi jurnalis asing untuk meliput di Indonesia.
Hadirnya
pasal penghinaan kepala negara dalam draf rancangan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) yang diusulkan pemerintah dan masih adanya aturan
kriminalisasi pengguna internet dalam revisi Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE), semakin menguatkan kesan pemerintah
mengekang kebebasan pers dan berekspresi.
Dan yang baru saja muncul pada Desember 2015 adalah hadirnya RUU Contempt of Court (penghinaan pengadilan).
Pada
RUU itu diatur ancaman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah),
bagi siapa saja yang mempublikasikan proses persidangan, dan dinilai
bertendensi atau mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak
hakim. Sebuah pasal karet terancam hadir di Indonesia.
Kemudian
pernyataan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso juga patut
dicermati. Jenderal purnawirawan ini menyatakan, pemerintah harus
mengawasi media massa.
Komitmen pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat untuk memperbaiki keadaan juga minim. Revisi
Undang-undang ITE yang ditargetkan bisa tahun ini untuk menghilangkan
pasal kriminalisasi atas pengguna Internet berhenti di jalan.
Terakhir,
draf revisi yang disusun Kementerian Komunikasi dan Informatika
ternyata belum sampai ke tangan DPR, masih berada di tangan Kepala
Kepolisian.
“Pembahasan rancangan undang-undang
Penyiaran dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia juga jalan di
tempat. Tidak selesainya pembahasan dua RUU ini tentu akan menghambat
proses migrasi televisi dari sistem analog ke digital,” tutup Suwarjono.
(rhm)